This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.

Sejarah Marga Catatan sejarah marga (dipadankan menjadi clan / klan) dapat ditarik kembali jauh sampai ke masa penyebaran awal manusia di bumi. Biologi melalui genetika mencatat bukti tersebut melalui alur perpindahan gen manusia-manusia sekarang yang memenuhi seluruh pelosok dunia. Dari catatan tersebut dapat diketahui pola perpindahan tersebut melalui pola-pola gen dan DNA (Deoxyribonucleic acid) manusia hingga kepada pembentukan ras manusia. Marga atau klan merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan dalam silsilah/leluhur atau memiliki hubungan darah antara anggota yang satu dengan lainnya, meski saat ini hubungan tersebut hanya terwakili oleh nama depan atau nama belakang yang disandang. Hal ini bisa ditemukan dalam sistem kemargaan Batak dan Minahasa—atau yang lebih jauh Jepang dan Cina. Klan, sejauh ini, didominasi oleh garis keturunan dari bapak/ayah; sementara hanya sebagian kecil yang ditarik dari garis ibu (misalnya pada suku Indian Amerika), sementara sebagian kecil lainnya mengambil garis dari perpaduan ibu dan ayah, seperti pada suku asli Armenia dan sebagian suku Arab. Mengapa klan terbentuk? Sampai saat ini jawaban untuk pertanyaan tersebut hanya didasari oleh identifikasi dan persepsi manusia sekarang terhadap kemungkinan dan manfaat yang dapat dihasilkan dari sebuah klan atau marga terkait kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup dan berketurunan. Manfaat tersebut antara lain: superioritas, keutuhan darah—yang kemudian membentuk hierarki atas dan bawah, keamanan, dan identitas—baik itu wilayah maupun kekuasaan. Dari fase inilah sebetulnya sejarah manusia mulai dicatat, antara lain, melalui penulisan silsilah keluarga marga dan sejarah masing-masing orang yang ada di dalam silsilah tersebut. Penulisan silsilah tersebut, di samping untuk mempertahankan “kesucian” garis marga, juga untuk menghindari perkawinan antarsesama marga yang sangat bertolak belakang dengan tujuan pembentukan marga dalam usaha memperluas jaringan kefamiliannya. Penulisan silsilah marga sebagai pertahanan nilai dan kekuatan sebuah marga, di samping dilihat dari sisi kekayaan dan kekuasaan yang memengaruhi teritori, juga memengaruhi nilai hitung kekuatan dari jumlah anggota marga yang dapat dimobilisasi untuk tujuan perburuan dan perang. Sejarah Marga (Klan) di Nusantara dan Hubungannya dengan Budaya di Nusantara Sejauh ini, pengertian dari marga di Nusantara tidak berbeda jauh dengan pengertian klan di luar negeri—karena bukankah saat ini ilmu pengetahuan modern dirumus dan dikembangkan oleh filsuf dan ilmuwan Barat. Yang menarik di Nusantara adalah keragaman pola marga itu sendiri, sebagai salah satu sisi budaya yang terbentuk. Perkawinan antarmarga menimbulkan berbagai ritual budaya yang berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan dan kekuatan, sehingga di banyak budaya klan di Nusantara terdapat istilah “jual-beli” perkawinan. Pihak perempuan atau sebaliknya akan ditukar dengan sejumlah nilai kekuatan dan kekuasaan lain sebagai ganti hak penurunan nama marga yang dihilangkan dari calon-calon keturunannya kelak. Yang menarik selanjutnya adalah pola teritorial, di mana klan-klan di Nusantara biasanya memiliki kawasan dan teritori masing-masing dengan hukum dan aturan masing-masing, meski masih dalam area yang sama. Para Prajurit Nias berkumpul di depan “omo Sebua” (kediaman pemimpin Desa) Berbicara mengenai sejarah marga di Nusantara masih merupakan misteri—selain yang dapat diperoleh dari catatan-catatan asli penduduk lokal yang masih ada, dan beberapa di antaranya merupakan tradisi tutur, yang oleh sebagian besar ilmuwan tidak dapat dianggap sebagai sebuah data atau fakta yang dapat dijadikan rujukan utama sebuah penelitian, karena dianggap memiliki banyak bias yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tradisi tutur tersebut biasanya menceritakan asal-usul marga sebagai sebuah cerita dan melegenda di kalangan masyarakat yang bersangkutan. Legenda tersebut, dengan tujuan mengangkat derajat leluhur, seringkali dikait-kaitkan dengan sang prima causa itu sendiri, sehingga kedudukannya sejajar dalam aturan dan hukum yang berlaku dalam klan tersebut. Dari sinilah sebetulnya budaya Nusantara dibentuk secara utuh; aturan, nilai, dan norma yang dibentuk atas jalinan manusia-lingkungan-alam menemukan bentuknya-kendati bentuk tersebut tidak tercatat dalam media baca-tulis namun nilai dan norma tersebut diterapkan dalam kehidupan keseharian masyarakat Nusantara hingga ke dalam bentuk gestur atau gerak tubuh-sebuah pencapaian puncak ideologi. Pandita sebagai strata tertinggi di Bali Dari nilai dan norma yang kemudian membentuk aturan dan hukum tersebutlah, sesungguhnya garis dan batas imajiner masyarakat Nusantara dapat dikenali, di mana kesamaan keunikan tersebut hanya dapat ditemui pada wilayah-wilayah sebagian besar Asia Tenggara, di mana aturan dan hukum telah mencapai titik puncak sebuah peradaban; dengan kata lain, nilai-nilai tersebut telah mendarah daging. Potensi Marga/Klan sebagai Penjaga Budaya Dari uraian sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa marga merupakan pembentuk awal dari budaya-budaya yang berkembang selanjutnya—entah melalui percampuran maupun perkembangan zaman. Seyogyanya, marga merupakan penghasil sekaligus penjaga kelangsungan dari budaya, karena tanpa nilai dan norma, sebuah marga akan kehilangan hakikat dari marga yang sesungguhnya, pun pada saat ini banyak marga yang sudah kehilangan tujuannya dan hanya berfungsi sebagai pengenal saja tanpa ikatan lainnya. Anggota suku Sakuddei (Mentawai) mengadakan upacara. Kini, di Indonesia – Negara yang meng-klaim sebagai pewaris Nusantara, orientasi dari ikatan kemargaan telah bergeser ke titik yang makin melenceng dari tujuan semua dari pembentukan marga. Sebuah marga, dari yang semula bersifat suci bergeser menjadi kegengsian yang eksklusif nan kabur. Nama marga lantas dijadikan benteng keakuan untuk menafikan realitas marga lain. Kemargaan, oleh sebagian orang, dilembagakan dalam sebuah wadah organisasi massa yang terdiri atas etnis tertentu dan atau agama (keyakinan) tertentu, di mana teritorial marga yang satu dibenturkan dengan wilayah marga lain. Terjadi pertentangan antara marga satu dengan marga yang lain, dan ini dipicu oleh struktur sosial yang berubah. Yang terjadi kemudian adalah perbauran nilai kemargaan dengan kepentingan yang sungguh berada di luar lingkaran nilai kemargaan. Sistem kemargaan, pada gilirannya, menjadi tunggangan kaum-kaum tertentu yang memiliki kepentingan politis atau bahkan agama, dan bukan lagi perwujudan kerukunan dan kebersamaan yang etis. Ia telah dibatasi oleh determinasi sempit di mana etnis satu dibenturkan dengan etnis lain, yang pada hakikatnya mengabaikan potensi marga sebagai penjaga dan pelestari budaya – yang nampak justru adalah kelompok-kelompok yang tidak memiliki budaya sama sekali. Hal ini jelas akan memperkeruh kejernihan nurani dan akal yang sejatinya merupakan landasan terciptanya sebuah kemasyarakatan yang adil dan beradab serta penuh dengan keakuran dan keselarasan. Salam Nusantara!

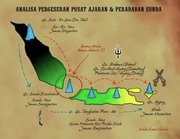

 Print this page
Print this page RSS Feed
RSS Feed
